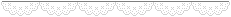Kita semua pasti setuju bahwa kata 'kreatifitas' biasanya dihubungkan dengan hal-hal yang positif. Contohnya, orang-orang yang kreatif biasanya memiliki ide-ide yang inovatif dan cara berpikirnya-pun 'beda' dengan orang kebanyakan (atau kalo guru TIK-ku bilang berpikir bercabang-cabang :p). Tapi, terkadang kreatifitas yang seharusnya bersifat positif itu bisa dilakukan di tempat yang salah.
Contoh yang mudah untuk menjelaskan bahwa orang kreatif itu terkadang salah tempat adalah meja. Lho kok meja? Nah, kita semua yang pernah merasakan duduk di bangku sekolah, pastinya pernah melihat paling tidak satu-dua coretan atau gambar di meja sekolah kita, kan? Kalau cuma coretan bolpoin karena tidak sengaja, mungkin bisa dimaklumi. Tapi seringnya, coretan tersebut sudah tidak bisa digolongkan ke dalam kategori tidak sengaja...karena bentuknya gambaran atau tulisan macam "Spongebob <3 Dora" atau yang lebih alay dan parah "sms aku ea 086066XXXXX".
Kebetulan aku juga masih menjadi siswa kelas IX di SMP PIUS BAKTI UTAMA GOMBONG, otomatis aku masih berhubungan sama yang namanya kelas komplit beserta meja kursi di dalamnya. Setahun yang lalu, pihak sekolah mulai memberlakukan "Moving Class" jadi yah...lumayan lah kelasnya bisa pindah-pindah, dan kami nggak harus menetap di kelas yang sama selama satu tahun. Tapi kerugian dari moving class tersebut, siswa jadi merasa makin 'bebas' untuk mencoret-coret meja karena kemungkinan ketahuannya kecil sekali (soalnya kelas pindah-pindah sesuai mata pelajaran). Dan hampir semua meja di sekolahku tidak luput dari coretan satupun. Kalo di atas meja sedikit coretannya, coba periksa di laci... karena "orang kreatif" yang masih malu-malu, biasanya lebih suka menuangkan pikirannya di tempat yang agak tersembunyi.
Jujur, kalau lagi bosen di kelas, aku suka memperhatikan coretan-coretan di meja yang kutempati. Kadang coretan tersebut hanya sebuah inisial nama atau motif hati yang sangat absurd. Tapi sekarang, coretan tersebut sudah berkembang menjadi ringkasan suatu materi pelajaran (mungkin buat contekan kali, ya?), gambaran kartun, atau semacam pesan yang ditujukan kepada seseorang (hellooo? it's 2014, dude. email ada, facebook, twitter, hp juga ada. ngapain repot-repot nulis pesan di meja? *facepalm*). Tidak jarang juga aku menemui coretan berupa makian yang ditujukan kepada seseorang, bahkan gambar-gambar porno dilengkapi kata-kata jorok. Miris! Inikah cermin pelajar sekarang ini? Padahal jelas-jelas tertulis di buku tata tertib sekolah bahwa mengotori sarana pra sarana sekolah (termasuk meja-kursi) akan dikenakan poin 5 dan diharuskan untuk membersihkan fasilitas sekolah yang dikotori tersebut.
Mengotori fasilitas sekolah saja sudah termasuk pelanggaran, jika ditambah dengan meneror / melakukan bullying, berarti melakukan double pelanggaran. Nah, itulah yang sedang marak baru-baru ini, yaitu meneror melalui meja di kelas-kelas. Modusnya adalah menuliskan pesan teror dengan mencantumkan nama orang yang dituju di meja yang sekiranya sering ditempati oleh yang bersangkutan. Hal tersebut tentu menjadikan kita yang tidak sengaja membaca pesan teror tersebut merasa risih dan terganggu.
Usaha yang dilakukan pihak sekolah menurut saya juga sudah lumayan banyak. Mengampelas meja sudah berkali-kali dilakukan. Namun, coretan tersebut sifatnya seperti parasit, satu dihapus, maka akan muncul lebih banyak coretan di tempat lain.
Dan, coretan-coretan itu seolah adalah budaya turun temurun. Jadi sekalipun generasi "kreatif" tersebut sudah lulus semua, pasti muncul generasi penerus yang baru. Dengan begini, coretan-coretan di meja tersebut tidak akan ada habisnya dan mungkin malah bertambah "kreatif". Tentu budaya yang seperti ini bukan budaya yang pantas diturunkan kakak kelas kepada adik-adiknya.
Aku percaya, oknum-oknum pencoret meja tersebut sebenarnya orang-orang kreatif. Hanya saja, mereka belum dapat membedakan mana media yang seharusnya mereka gunakan untuk menuangkan ide-ide mereka itu. Bisa jadi karena media yang mereka gunakan untuk "kanvas" mereka kurang, jadi tangan jail mereka mulai merambah ke tempat yang lain seperti meja kelas, contohnya. Bisa juga karena kurangnya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki. Kedua hal tersebut dapat terjadi salah satunya karena "moving class" ini membuat siswa merasa tidak bertanggung jawab terhadap kelas yang ditempatinya karena hanya sekadar "numpang" dan bukan merupakan kelas miliknya. Padahal harusnya kita sebagai warga sekolah secara alami merasa bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kenyamanan sekolah kita, baik itu moving class maupun tidak. Dan, kreatif memang baik apabila di tempat yang tepat dan kreatif mengenai hal yang tepat pula.
Friday 26 September 2014
Friday 12 September 2014
Serial Story : The Ghost Lover.
The Ghost Lover
by Nadine Orionna
CHAPTER ONE : CAN YOU SEE ME?
Perkumpulan yang kuhadiri setiap hari sepulang sekolah memang sedikit konyol. Maksudku, perkumpulan tersebut dihadiri oleh orang-orang yang sama setiap harinya dan topik yang dibicarakan juga selalu sama. Konyol memang, tapi aku tidak pernah absen dan di sinilah aku sekarang, di rumah Emily bersama dengan Abigail, Diana, dan Georgia yang duduk membentuk sebuah lingkaran kecil.
"Hey, kau tahu kalau Liam sekarang ini dekat dengan Isabelle?" ujar Georgia membuka 'pertemuan' konyol kami. Semua terdiam, entah berpikir bahwa informasi Georgia tidak penting, atau berpikir bagaimana caranya pura-pura tertarik dengan informasi itu. Aku menghela napas panjang, seakan semua beban yang mengganjal dipikiranku akan runtuh hanya dengan satu tarikan napas saja. "Guys, ayolah... sekali-kali aku ingin membicarakan yang lain. Aku bosan menggosip tentang pasangan-pasangan di sekolah yang sedang tenar." akhirnya aku buka suara. Semua mengangguk, mengamini pernyataanku barusan. Meskipun tanpa anggukan dari mereka, aku yakin mereka setuju. Kau tahu kan kata orang dulu bahwa seorang sahabat, meskipun tidak berkata-kata akan tetap memahami sahabatnya? kurasa itu yang kualami saat ini.
"Baiklah, kebetulan aku ingin melengkapi data penelitianku. Jadi aku membutuhkan beberapa jawaban dari kalian." Emily mengeluarkan setumpuk kertas dari file-holder merah muda miliknya.
"Pertama-tama, Caitlin, apa ketakutan terbesarmu?" Aku merapatkan bibir, menahan kata 'ketinggian' keluar dari mulutku. Sejak kecil aku memang tidak bisa berdiri di atas ketinggian lebih dari tiga meter. Aku pernah membaca di sebuah brosur kesehatan bahwa ketakutan seperti itu disebut phobia dan sampai saat ini belum ada obatnya kecuali pikiran kita sendiri. "Ketinggian" kataku. Setelah kupikir-pikir takut ketinggian bukanlah hal yang memalukan, mengingat banyak juga orang dewasa yang takut pada ketinggian.
"Jadi kau tidak takut hantu, monster, atau sejenisnya?"
"Tidak. Memang kenapa? hal semacam itu munculnya hanya dari pikiranmu saja. Mereka tidak nyata" jawabku enteng. "Oya, memang penelitian macam apa ini?"
Emily menuliskan beberapa kalimat di kertasnya lalu memandangku heran. "Memangnya aku belum cerita kalau klub karya ilmiah-ku menugaskan aku untuk membuat penelitian tentang jenis ketakutan seseorang?" Emily malah balik bertanya. Aku mengangkat alis, menampakkan wajah menyerah. Kadang banyak hal yang kupikirkan sampai aku melupakan hal-hal kecil seperti klub karya ilmiah Emily. Kami berlima adalah gadis dengan kepribadian yang sangat bertolak belakang. Abigail adalah pecinta seni, buku matematika bagian belakangnya penuh dengan coretan gambar-gambar aneh. Diana dan Georgia, bagi mereka tiada hari tanpa menggosip! Artis, bintang sekolah, cowok, sampai orang paling tidak populer di sekolah saja mereka jadikan bahan menggosip. Kalau gadis berkacamata dengan rambut ekor kuda di hadapanku ini, dia penggila ilmu pengetahuan. Emily bahkan masuk ke ekstrakurikuler yang tidak diminati oleh anak-anak kebanyakan, Karya Ilmiah Remaja. Dan aku? Biasa. Setidaknya hanya itu yang bisa kudeskripsikan dari diriku. Segala aspek diriku kesannya sangat biasa. Tidak menonjol. Meski begitu, kami sudah bersahabat selama tujuh tahun, aku sendiri tidak mengerti apa yang menjadikan persahabatan kami bertahan sangat lama.
Biasanya kami melakukan pertemuan ini selama dua jam, berarti ini waktunya aku pulang.
nadineorisu.blogspot
Hawa dingin langsung menyergap ketika aku keluar dari rumah Emily. Musim gugur adalah salah satu musim yang tidak kusukai. Hujan kadang tiba-tiba datang tanpa dapat diduga, seperti saat ini. Jalanan ramai dipenuhi pegawai kantoran yang baru pulang bekerja. Kebisingan kendaraan berpadu dengan suara air hujan yang membentur tanah. Suasana kota seperti ini yang seringkali membuatku berpikir untuk pindah kota saja ketika aku lulus SMU. Jarak rumahku dengan rumah Emily dapat ditempuh dalam waktu sepuluh menit
dengan taksi, tapi dalam keadaan jalanan macet seperti ini kemungkinan perjalanan akan dua kali lipat lebih lama. Lagipula, taksi pasti dipenuhi oleh pekerja kantoran yang akan pulang ke rumah Akhirnya jalan kaki menjadi pilihan terakhirku. Untung saja aku tidak membawa buku-buku penting di dalam tas, sehingga kehujanan tidak jadi masalah buatku.
Baru saja aku akan melewati Buckingham street, terdengar suara ledakan dari arah pukul tiga. Tapi suaranya tidak mirip sebuah ledakan, melainkan seperti suara tabrakan. Aku menoleh ke kiri, dan menemukan sebuah mobil berlumuran darah di bagian depan. Aku tidak dapat melihat apa yang ditabrak mobil sedan tersebut karena terlalu banyak orang mengerumuninya.
"Maaf nona, kau dapat melihat siapa yang ditabrak itu?" seseorang menepuk pundak kananku. Aku menggeleng tanpa menoleh. "Aku tidak tahu. Terlalu ramai disana" kataku, kali ini menatap orang tadi. Seorang lelaki yang tingginya kurang lebih delapan inci di atasku menunjukkan air muka cemas. Rambut pirang gelapnya terlihat acak-acakan dan kaus kelabunya basah karena keringat dan air hujan. Tidak lama setelahnya, kerumunan orang mulai berkurang. Aku memanfaatkannya untuk memuaskan hasrat ingin tahuku.
"Sepertinya ia sudah meninggal." "Sepertinya begitu." kedua orang wanita paruh baya tampak prihatin menatap mobil dihadapan mereka. Setelah kedua wanita tersebut menyingkir, aku bisa tahu apakah atau lebih tepatnya siapakah yang menjadi korban mobil sedan tersebut. Seorang pria terkapar di jalanan dengan motornya yang juga sudah setengah hancur.
nadineorisu.blogspot
"Yah.. ternyata aku telah mati" kata lelaki rambut pirang dibelakangku tadi. "Ma-maksudmu?" Aku menoleh dengan tatapan horor. Jantungku berdegup kencang. Seorang polisi melepas helm si korban tabrakan, dan tampaklah wajah lelaki dengan rambut pirang. Ciri-cirinya sama dengan orang asing yang baru berbicara denganku. Seorang polisi datang lagi dan meraba-raba leher kiri korban. Setelah beberapa kali mengecek, akhirnya mereka memasukkan korban ke dalam kantong berwarna kurning, kantong jenazah."Aku baru saja tabrakan, semuanya terasa hitam dan ketika aku bangun, aku dapat melihat tubuhku terkapar di jalanan" pria tadi kembali buka suara. Perutku serasa dihantam sesuatu yang keras. Jika pria ini sudah meninggal, lalu aku berbicara dengan siapa? Pikiran-pikiran bergulat di benakku. Rasanya tidak masuk akal.
"Hey tunggu. Kau berbicara denganku. Kau bisa melihatku?" lelaki tadi membelalakkan mata, tak percaya. Jantungku berdebar sangat kencang, aku yakin sebentar lagi pasti jantungku meledak.
to be continued...
Friday 5 September 2014
BOOK REVIEW : The Fault In Our Stars
As a book hunter, The Fault In Our Stars a.k.a TFIOS pasti nggak asing. Apalagi setelah film layar lebar berjudul sama melejit di box office. Semua orang, terutama para remaja cewek, SEMUANYA ngomongin tentang TFIOS. Bahkan sebelum film-nya ditayangkan di bioskop! Tapi sedihnya, banyak yang nggak tau kalau film yang mereka tonton itu sebenarnya diadaptasi dari novel karangan John Green. Aku sendiri baru selesai membaca novel itu sekitar beberapa bulan yang lalu. Waktu itu, banyak review-review bagus tentang novel tersebut dan bikin aku cukup penasaran. TFIOS sendiri terbit pada bulan Januari 2012, dan waktu itu menjadi best seller internasional. Emang agak telat sih, soalnya aku sendiri baru tau TFIOS di awal 2014 dan waktu itu aku beli yang versi internasional / pake bahasa inggris. Tanya kenapa? karena aku dari awal memang nggak minat untuk beli yang versi bahasa indonesia, bukan karena mau gaya-gayaan, tapi covernya ituloh-_- bukan cover originalnya, malah lebih ke arah buku cerita anak-anak daripada novel young-adult karangan seorang John Green . Dan yang lebih parah lagi, terjemahannya bikin kita garuk tembok. Anyway, meskipun di luar sana sudah banyak orang yang memberikan review tentang buku ini, aku akan tetap menulis review versi-ku sendiri.
Seperti yang bisa kalian tebak, The Fault In Our Stars memang mengisahkan tentang penderita kanker. Tapi ini bukan seperti cerita kanker biasanya, percayalah ;). Pujian pantas dialamatkan kepada John Green, karena tokoh Hazel Grace Lancaster sebagai seorang pencerita dalam novel ini dapat tergambarkan dengan baik. Ketika membaca TFIOS, kita benar-benar dapat mendalami emosi seorang Hazel sebagai seorang gadis 16 tahun dengan tumor di paru-parunya. John Green juga sukses membuat Augustus Waters pantas
dinobatkan sebagai salah satu best fictional boyfriend.
TFIOS juga membuat mataku berair bukan sekali-dua kali saja, tapi sering! Puncaknya pada waktu Hazel membacakan eulogy-nya untuk Gus pada waktu pre-funeralnya Gus. Novel ini dipenuhi dengan bumbu humor sarkastik dimana-mana. Dan pada versi inggrisnya, tidak banyak bagian yang dipotong / disensor karena penggunaan kata yang kurang sopan. Justru karena itulah yang membuat TFIOS menarik. Sisi blak-blak an John Green itulah yang bukannya membuatku risih, tapi jadi semakin tertarik dengan novel tersebut.
Meskipun beberapa kali menangis, Hazel sendiri bukanlah tipe cewek yang lemah. Dan keinginannya untuk meninggalkan kesan di dunia ini sebelum dia meninggal sangat membuat terkesan.
Tapi dugaanku tentang tokoh Peter Van Houten kayaknya agak meleset. Dan pada bagian dimana Peter menolak Hazel dan Gus waktu mereka mengunjungi Peter di Amsterdam bikin aku (dan pastinya kalian juga) pengin banget mencekik dia-_- serius!
Dan ketika aku sampai di halaman akhir, what the heck? secepat itukah? ketika sampai di halaman-halaman akhir rasanya berat sekali berpisah dengan novel amazing ini. Memang banyak yang bilang kalau TFIOS ini ending-nya gantung. Tapi nggak juga menurutku. Surat Augustus kepada Peter Van Houten tentang Hazel sangat pas sebagai penutup dari novel ini. Quotes yang tersebar dimana-mana di novel ini. Novel ber-cover biru ini juga berhasil membuktikan bahwa cerita tentang remaja bukan cuma cerita kosong yang bodoh dan tidak berbobot, tapi juga cerdas dan menginspirasi.
Jujur saja, ketika menonton film TFIOS, aku agak kecewa. Banyak adegan-adegan dalam novel yang tidak ada dalam film-nya. Tapi overall, film yang dibintangi Shailene Woodley, Ansel Elgort, dan Nat Wolff itu sudah sangat bagus. Shailene benar-benar menggambarkan sosok Hazel, namun Ansel sepertinya tidak terlalu cocok dengan perannya sebagai Gus. Bukan karena aktingnya yang tidak maksimal, tapi lebih ke penampilan fisiknya. Dalam novel, berkali-kali disebutkan bahwa Gus memiliki mata yang biru, nah pertanyaannya, di mana mata biru yang bikin Hazel tertarik itu? Haha. Tidak sampai disitu saja, tokoh Isaac yang diperankan oleh Nat Wolff benar-benar berbeda seperti apa yang kubayangkan sewaktu membaca novelnya. Rambut blonde Isaac dan tubuh kurusnya sama sekali tidak ada dalam Nat.
Tapi bagian di mana Hazel membacakan eulogy-nya untuk Gus pas pre-funeralnya si Augustus, tetep sukses bikin aku nangis~ Setting Amsterdam di film juga kurang lebih sama kayak yang aku bayangin waktu baca novelnya.
Soundtrack yang ada di film TFIOS juga asik-asik. Terutama Ed Sheeran - All Of The Stars, aaawww!
Well, semoga review-ku tentang TFIOS ini bisa ngasih referensi buat kalian :))) see ya next time!
"My life is a roller-coaster that only goes up" -John Green
Seperti yang bisa kalian tebak, The Fault In Our Stars memang mengisahkan tentang penderita kanker. Tapi ini bukan seperti cerita kanker biasanya, percayalah ;). Pujian pantas dialamatkan kepada John Green, karena tokoh Hazel Grace Lancaster sebagai seorang pencerita dalam novel ini dapat tergambarkan dengan baik. Ketika membaca TFIOS, kita benar-benar dapat mendalami emosi seorang Hazel sebagai seorang gadis 16 tahun dengan tumor di paru-parunya. John Green juga sukses membuat Augustus Waters pantas
dinobatkan sebagai salah satu best fictional boyfriend.
TFIOS juga membuat mataku berair bukan sekali-dua kali saja, tapi sering! Puncaknya pada waktu Hazel membacakan eulogy-nya untuk Gus pada waktu pre-funeralnya Gus. Novel ini dipenuhi dengan bumbu humor sarkastik dimana-mana. Dan pada versi inggrisnya, tidak banyak bagian yang dipotong / disensor karena penggunaan kata yang kurang sopan. Justru karena itulah yang membuat TFIOS menarik. Sisi blak-blak an John Green itulah yang bukannya membuatku risih, tapi jadi semakin tertarik dengan novel tersebut.
Meskipun beberapa kali menangis, Hazel sendiri bukanlah tipe cewek yang lemah. Dan keinginannya untuk meninggalkan kesan di dunia ini sebelum dia meninggal sangat membuat terkesan.
Tapi dugaanku tentang tokoh Peter Van Houten kayaknya agak meleset. Dan pada bagian dimana Peter menolak Hazel dan Gus waktu mereka mengunjungi Peter di Amsterdam bikin aku (dan pastinya kalian juga) pengin banget mencekik dia-_- serius!
Dan ketika aku sampai di halaman akhir, what the heck? secepat itukah? ketika sampai di halaman-halaman akhir rasanya berat sekali berpisah dengan novel amazing ini. Memang banyak yang bilang kalau TFIOS ini ending-nya gantung. Tapi nggak juga menurutku. Surat Augustus kepada Peter Van Houten tentang Hazel sangat pas sebagai penutup dari novel ini. Quotes yang tersebar dimana-mana di novel ini. Novel ber-cover biru ini juga berhasil membuktikan bahwa cerita tentang remaja bukan cuma cerita kosong yang bodoh dan tidak berbobot, tapi juga cerdas dan menginspirasi.
Jujur saja, ketika menonton film TFIOS, aku agak kecewa. Banyak adegan-adegan dalam novel yang tidak ada dalam film-nya. Tapi overall, film yang dibintangi Shailene Woodley, Ansel Elgort, dan Nat Wolff itu sudah sangat bagus. Shailene benar-benar menggambarkan sosok Hazel, namun Ansel sepertinya tidak terlalu cocok dengan perannya sebagai Gus. Bukan karena aktingnya yang tidak maksimal, tapi lebih ke penampilan fisiknya. Dalam novel, berkali-kali disebutkan bahwa Gus memiliki mata yang biru, nah pertanyaannya, di mana mata biru yang bikin Hazel tertarik itu? Haha. Tidak sampai disitu saja, tokoh Isaac yang diperankan oleh Nat Wolff benar-benar berbeda seperti apa yang kubayangkan sewaktu membaca novelnya. Rambut blonde Isaac dan tubuh kurusnya sama sekali tidak ada dalam Nat.
Tapi bagian di mana Hazel membacakan eulogy-nya untuk Gus pas pre-funeralnya si Augustus, tetep sukses bikin aku nangis~ Setting Amsterdam di film juga kurang lebih sama kayak yang aku bayangin waktu baca novelnya.
Soundtrack yang ada di film TFIOS juga asik-asik. Terutama Ed Sheeran - All Of The Stars, aaawww!
Well, semoga review-ku tentang TFIOS ini bisa ngasih referensi buat kalian :))) see ya next time!
"My life is a roller-coaster that only goes up" -John Green
source : sailortimonline.com
source : +Instagram itsnadineorionna
Subscribe to:
Posts (Atom)